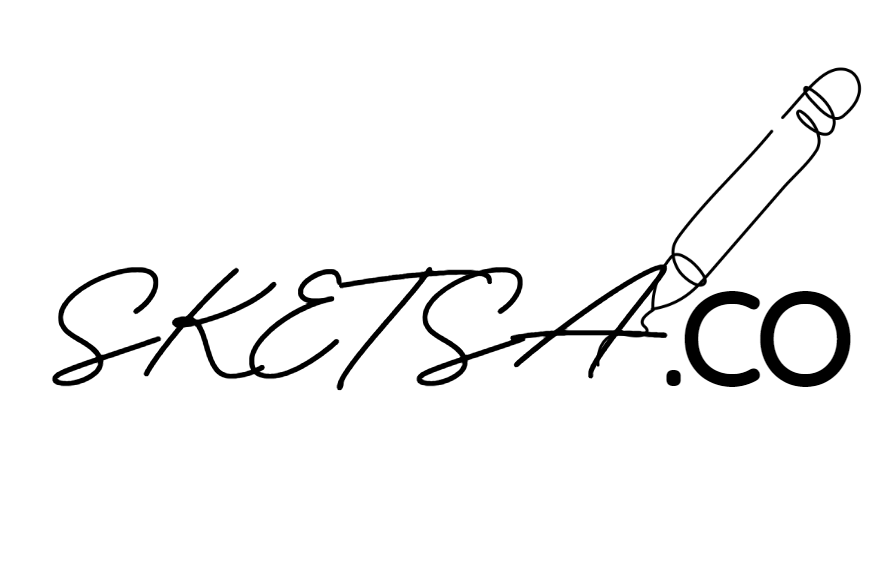JAKARTA (Sketsa.co): Berakhirnya Pilpres 2024 tidak serta-merta mengakhiri dinamika politik nasional di Tanah Air. Justru, setelah Prabowo Subianto ditetapkan sebagai presiden terpilih, muncul pembelahan wacana yang cukup menarik di ruang publik, yakni antara kubu yang dianggap “pro Prabowo” dan kubu yang disebut “pro Jokowi”. Keduanya sering dipersepsikan saling berhadapan, meski dalam praktiknya relasi politik di antara para elite jauh lebih cair dan kompleks daripada sekadar dikotomi hitam-putih.
Kubu pro Prabowo umumnya dipahami sebagai kelompok yang mendukung kepemimpinan Prabowo dengan penekanan pada citra kemandirian, ketegasan, dan nasionalisme. Narasi yang dibangun menempatkan Prabowo sebagai pemimpin dengan legitimasi elektoral kuat yang tidak lagi berada di bawah bayang-bayang siapa pun, termasuk Presiden ke-7 Jokowi . Pendukung di kubu ini kerap menekankan bahwa kemenangan Prabowo adalah hasil perjalanan politik panjang, konsistensi, dan penerimaan publik terhadap gagasan stabilitas, ketahanan nasional, serta keberlanjutan pembangunan dengan gaya kepemimpinan yang lebih tegas.
Di sisi lain, kubu pro Jokowi merujuk pada kelompok yang masih melihat Jokowi sebagai figur sentral dalam politik Indonesia, bahkan menjelang dan setelah akhir masa jabatannya. Mereka menilai Jokowi bukan hanya presiden dua periode, tetapi juga aktor politik dengan pengaruh besar dalam menentukan arah kekuasaan, konfigurasi koalisi, dan regenerasi kepemimpinan. Keberhasilan pembangunan infrastruktur, pendekatan teknokratis, serta gaya komunikasi populis Jokowi dianggap sebagai “modal politik” yang ingin terus dijaga dan dilanjutkan melalui figur-figur yang dekat dengannya.
Ketegangan Naratif
Ketegangan naratif antara kedua kubu ini sering muncul dalam perdebatan soal sejauh mana Prabowo akan “mandiri” sebagai presiden. Kubu pro Prabowo cenderung sensitif terhadap anggapan bahwa pemerintahan mendatang hanyalah perpanjangan tangan Jokowi. Bagi mereka, narasi semacam itu berpotensi mereduksi legitimasi Prabowo dan mengabaikan mandat rakyat yang diperolehnya melalui pemilu. Karena itu, muncul dorongan agar Prabowo tampil dengan kebijakan, gaya komunikasi, dan keputusan politik yang jelas mencerminkan kepemimpinannya sendiri.
Sementara itu, kubu pro Jokowi melihat kesinambungan sebagai hal yang wajar dan bahkan penting. Mereka berargumen bahwa stabilitas politik dan ekonomi membutuhkan transisi yang mulus, bukan pemutusan drastis. Dalam pandangan ini, kedekatan Prabowo dengan Jokowi justru dianggap sebagai jaminan bahwa program-program strategis nasional tidak akan terhenti atau berubah secara ekstrem. Jokowi diposisikan sebagai “mentor politik” yang pengalamannya masih relevan bagi pemerintahan baru.
Di tingkat akar rumput dan media sosial, polarisasi ini sering kali tampak lebih tajam daripada di level elite. Pendukung garis keras di masing-masing kubu kerap saling menyerang dengan tuduhan loyalitas ganda, pengkhianatan, atau bahkan manipulasi kekuasaan. Padahal, jika ditelisik lebih dalam, banyak aktor politik yang secara pragmatis berada di antara dua kutub tersebut, menyesuaikan sikap dengan kepentingan dan dinamika kekuasaan yang terus berubah.
Menariknya, Prabowo dan Jokowi sendiri cenderung menampilkan hubungan yang relatif harmonis di ruang publik. Hal ini menunjukkan bahwa konflik “kubu pro Prabowo versus kubu pro Jokowi” lebih banyak hidup sebagai konstruksi wacana ketimbang pertarungan terbuka antarfigur utama. Elit politik memahami bahwa stabilitas pemerintahan awal sangat bergantung pada kesan solid dan saling mendukung.
Ke depan, garis pemisah antara kedua kubu ini kemungkinan akan ditentukan oleh kebijakan konkret. Jika Prabowo mulai mengambil langkah-langkah yang berbeda secara signifikan dari era Jokowi, narasi kemandirian akan menguat. Sebaliknya, jika kesinambungan lebih dominan, kubu pro Jokowi akan merasa pengaruhnya tetap relevan. Pada akhirnya, publiklah yang akan menilai apakah dinamika ini memperkaya demokrasi atau justru memperpanjang polarisasi politik pasca pemilu.